Penulis : Umbu Justin
Membaca demi memanusia

Segala sesuatu membaca. Membaca merupakan pusat eksistensi segala sesuatu, masing-masingnya dan totalitasnya. Berhenti membaca, berhenti sebagai sesuatu; berhenti mengada, hilang begitu saja ?
Salah satu syair kuno Yunani tentang penciptaan bertutur bahwa Sang Pencipta itu, yakni Dia yg mula-mula adalah Kata. Kata merupakan bacaan.
Semesta adalah peristiwa membaca yang tak pernah usai. Berhenti membaca, semesta pun berakhir. Daya-daya purba semesta membaca kepadatan gravitasi tak berhingga, membaca menggunakan bunyi ledakan keras, dentuman purba, big-bang, tanggal memancar, meluas menciptakan ruang tak bertepi sampai sekarang. Semesta, cerita mengenai pembaca setia, membaca pesan intrinsik dalam dirinya dan membacakan lahirnya kejadian-peristiwa baru, semesta-semesta baru, daya-daya baru, pusaran-pusaran cakram galaksi baru; berada, melenyap dan berpendar mengada lagi, semesta yang terus lahir, menjadi remaja, dewasa, menua & tewas menggunakan letusan brilian sebagai hembusan kabut gas warna-warni & kepingan-kepingan mineral, emas, perak, besi, tembaga dan air raksa sebelum melapuk hanyut pada lautan luas ruang tak berbatas atau berlanjut ditarik ke dalam pusaran-pusaran galaksi baru.
Terjadinya semesta tidak seperti narasi penciptaan biasa di mana sang pencipta sanggup kemudian memberikan karyanya pada etalase, memajang pada dinding atau menjualnya lalu melupakannya begitu saja. Semesta bertumbuh bagai pohon besar , meruang-luas, & akarnya menjangkau jauh ke pada hakekatnya sendiri, menimba pesan untuk terus berada menggunakan berevolusi memperbaharui diri.
Evolusi berarti mengatasi krisis, karena interaksi antar bentuk-bentuk usang nir lagi aktual, perlu adaptasi dan antisipasi buat menghadirkan bentuk-bentuk interaksi baru. Membaca bagi semesta berarti tindakan menjawab krisis, berubah menuju dinamika relasional baru.
Lahirnya kehidupan, dalam konteks kita, adalah narasi beragam. Bumi memiliki kemiringan sumbu dan jeda yg pas terhadap mentari , sehingga air padanya senantiasa cair, sebagai akibatnya bisa tercipta arus & pasang-surut akibat gravitasi bulan. Pembacaan berulang kali berjuta tahun, pasang-surut, arus samudera , rotasi, revolusi, siang-malam, pergantian demam isu, membacakan narasi baru: pemunculan kehidupan, sebuah narasi dengan intrikasi tenunan sebab dampak yg sangat kompleks; menurut situ tak ada yang bisa diurai, dilepaskan sebagai kalimat tunggal buat berdiri sendiri.
Dinamika semesta raya terus berubah menuju pembacaan yang semakin kompleks, berevolusi menuju kesadaran, conscientia, kehidupan berbudaya, sebuah pencapaian kesetimbangan baru dengan hadirnya mahluk berbudi bahasa…
Manusia, pengeja kesadaran, muncul menurut jalan panjang evolusi, berkutat membaca pesan semesta pada dirinya: mempertahankan hidup, bersosialisasi, bermigrasi, merespon bahaya, mengatasi permasalahan & seterusnya melalui kecakapan membaca intrinsik. Pada jutaan tahun pertama, setiap pengalaman insan merupakan reaksi pribadi, pada mana pengalaman nyata melekat erat dalam seluruh penginderaannya & dengan tubuhnya insan mengambil respon yg sinkron buat mempertahankan hidup.

Ia hadir dengan canggung sebab tubuhnya tidak 'selengkap' mahluk lain yang leluasa berhadapan dengan tantangan alam liar, tak berbisa, tidak ber-mimicri, tidak bertanduk atau memiliki cakar, tidak secepat , selincah yang lain. Manusia membutuhkan kecakapan sosial, kemampuan berinteraksi dalam keluarga, suku dan jaringan kebersamaan yang lebih kompleks. Manusia awal membutuhkan jenis pembacaan yang mendampingi pembacaan intrinsiknya, yakni daya baca abstrak, ekspresi dari conscientia, berupa tutur bahasa.
Beruntung insan awal berlindung pada gua-gua alam yg menjorok ke dalam perut tebing-tebing batu. Kegelapan gua sanggup 'mematikan' indera, melepaskan insan dari global luar yg sangat menyita perhatian. Manusia 'melihat' kegelapan, meraba kekosongan & mendengarkan keheningan. Kegelapan, loka berhenti bereaksi, tempat tetirah & merasakan global lain yang lebih luas, alam batiniah, tempat roh merogoh alih daya-daya jasmani menggunakan dinamika yang jauh lebih beraneka rona: refleksi, imajinasi & abstraksi.
Dalam kegelapan, mimpi dan imajinasi mendapatkan tempat, merasuk jauh ke pada dasar batin. Pengalaman luar gua, penginderaan total yg serba nyata, ada pulang menjadi gambar-gambar reflektif, tidak konkret, imajiner. Kegelapan gua menjadi jelas paling brilian bagi insan: ruang kesadaran baru, abstraksi, imajinasi, pelepasan diri dari kejasmanian menuju yang spiritual. Manusia mulai membaca dengan bahasa, reflektif, tanpa terikat pengalaman nyata global luar.
Gambar-gambar hewan dan grafis perburuan pada dinding gua-gua purba misalnya pada Altamira, adalah aktualisasi diri reflektif itu, lompatan akbar pada sejarah membaca. Kita melihat bison-bison di dinding gua berderap di padang-padang terbuka di batin kita. Imajinasi menjadi yg aktual.

Dalam gua gelap kita butuh konkretisasi pengalaman batin. Maka lahirlah gambar, simbolisasi yg melepaskan kita menurut persentuhan langsung dengan global luar dan sekaligus mengkonkretkan global batin. Simbol tidak terikat pada fenomena namun simbol sanggup mengarahkan respon manusia buat mengatasi krisis pada situasi nyata dengan lebih terjadwal. Simbol menyimpan fenomena dengan lebih aktual dibandingkan dengan peristiwanya sendiri. Simbol bison pada dinding gua menyimpan dan menghadirkan kesan tentang semua bison pada padang mana pun, yang sudah terdapat atau pun yg belum ada. Bagi para pemburu purba, gambar bison itu adalah seruan panggilan buat menghadirkan balik perburuan kawanan bison itu dalam saatnya, sebuah ujud pengharapan, doa atau mantra.
Sebelumnya kecerdasan membaca hanya berlangsung secara intrinsik, genealogis, dalam riwayat biologis badan kita, contohnya dalam tubuh yang berjalan tegak, penglihatan panoramik, tangan yang bebas untuk bisa menciptakan peralatan. Sementara abstraksi merupakan daya membaca yg baru, kita dapat berbahasa, menciptakan simbol-simbol & pertanda-pertanda, memberi nama dalam sesuatu, generalisasi, menghitung, menyimpulkan dan menciptakan prediksi. Yang terpenting, kita mampu membahasakan pengalaman supaya pengalaman itu bisa direka-ulang, diceritakan pulang.
Kemampuan menceritakan kembali, menghadirkan pengalaman konkret atau imajiner, merupakan perayaan sosial yg dulu sangat dihargai. Di kurang lebih barah unggun, pada bawah fresko bison & kuda-kuda purba rona-warni ataupun di verbal gua, pada bawah selimut bintang-bintang abadi, nenek moyang kita mendengarkan shaman atau tetua bercerita tentang riwayat kehidupan. Saat inilah daya membaca kita merumuskan arah & orientasi baru, yakni kebebasan dan kreativitas yang sungguh hidup menurut global batin kita. Membaca dengan bahasa membuat hayati tidak terikat pada urusan respon demi keamanan fisik, nafsu, makan atau kelaparan. Membaca menjadi perayaan, menjadi representasi kemanusiaan yang berbudi bahasa. Hidup datang-tiba sebagai lebih luas dari sekedar keberlangsungannya.
Kita mungkin lupa dalam daya baca intrinsik yang tersimpan pada memori jasmani kita, namun kita sudah mengangkat memori itu ke dalam daya ungkap bahasa & melahirkannya sebagai budaya. Beribu-ribu tahun sesudah api unggun di bawah fresko kawanan bison dan ringkik kuda purba, bahasa sudah sebagai semakin kompleks. Semesta tetap membaca secara dinamis, bintang-bintang dan galaksi akbar-mini masih mengalir deras, meruang dalam arus sungai penciptaan yg abadi, dan pilihan terhadap manusia menjadi mahluk simbolik atau mahluk berakal budi sebagai narasi yang paling menakjubkan.
Membaca Kritis : Antara Alice dan Pinocchio
Kita tidak pernah bisa membaca hal yang sama dua kali tetapi kita selalu membaca buat mencari memahami tentang satu hal saja, yakni kebenaran eksistensi kita.
"Segala sesuatu mengalir, semua berlaludanquot;, istilah Heraclitus, filsuf dari kota Efesus, Yunani kuno, "kita tidak pernah sanggup menginjakkan kaki di sungai yg sama."
Yang tak berubah adalah perubahan itu sendiri...
Parmenides, filsuf Yunani antik menurut Elea membaca bahwa semesta tidak bisa berubah, hanya kesan pada kita saja yang berubah, seluruh hal sama saja, pada kembali tampilan yg bervariasi dan berubah-ubah, terdapat hanya yg sama senantiasa.
Kita hidup saat ini, lebih dari 2500 tahun setelah Heraclitus dan Parmenides, di antara kedua kutub tersebut, antara mengejar perubahan yang sedemikian cepat dan kecenderungan untuk mempertahankan kenyamanan, keyakinan, nilai, kebenaran, dogma dan seluruh kehidupan. Dan dengan terjebak di antara kedua kutub tersebut kita sama sekali tidak sempat membaca dengan benar. Pada kutub Heraclitus, pembela perubahan, kita dikepung oleh tuntutan untuk meng-update pengetahuan dan cara hidup. Pengetahuan kita menjadi sangat ephemeral, berumur pendek, gampang kadaluarsa. Kita mengejar percepatan dengan bekerja lebih efisien, lebih mudah, lebih singkat namun tetap tak terpuaskan. Meski akses pada pengetahuan menjadi sangat mudah,semua menjadi tidak bernilai, tak sempat berakar, hati kita terganggu untuk mengejar percepatan.

Di kutub Parmenides, pembela kemapanan, lantaran hati kita goyah dan was-was, takut pada arus perubahan yang menyapu semua milik kita, maka kita menegaskan kemurnian iman, keyakinan, adat norma, nilai-nilai & dogma-dogma menantang semua percepatan perubahan.
Mari kita kembali ke gua-gua purba kita, ketika kegelapan membutakan mata kita dan membuka mata batin kita, memandang gambar-gambar polychromos: bison-bison dan kuda-kuda yang berlarian di savana hati kita, mencari keniscayaan jadinya suatu lingkupan dunia yang sungguh bisa dilepaskan dari gejala badaniah kita kita melalui proses kebahasaan. Bison di dinding gua, apakah ia sungguh mewakili semua bison yang pernah ada, yang akan ada, bison dari tanah liat, atau awan berbentuk bison di mata kanak-kanak dan semua yang kita anggap bison? Sebuah gambar, sebuah simbol, sebuah kata, sebuah nama, apakah sungguh menunjuk pada realitasnya?
Filsuf Plato dalam dialognya yang terkenal 'Cratylus' mengungkapkan: "Dalam kata Mawar, terkandung seluruh mawar?" Dalam kata Nil, membentang seluruh alur-genre sungai besar tersebut, semua keloknya yang mengukir tanah tandus afrika utara, seluruh bangsa yg mengikatkan sejarah mereka pada kesuburannya & timbul tenggelamnya dinasti-dinasti perkasa pembangun piramida. Sebuah istilah, benar-benar penuh daya cipta menakjubkan. Maka bahasa adalah mantra pemanggil global & setiap buku adalah semesta yang siap dilahirkan.
Tetapi pada pulang keajaiban kata, nama, gambar, simbol, masih ada sebuah dinamika kontras, meski mengikat & menghadirkan realitas, bahasa pun ternyata segera memisahkan insan dari semesta. Di luar gua manusia berhadapan menggunakan kesamaan pragmatis, buat menjamin keberlangsungannya, insan membutuhkan jarak yang memadai terhadap semesta, untuk bisa menghindari ketak-terdugaan peristiwa, & mengendalikan peristiwa-peristiwa, menciptakan prediksi, menciptakan perencanaan agar hanya yg diinginkan yg sanggup bermetamorfosis sebagai insiden. Manusia memisahkan diri berdasarkan totalitas semesta, menjadi individu dengan membentuk lingkungan yang bisa dikendalikan. Caranya merupakan menggunakan menciptakan bahasa menjadi sebuah instrumen. Gambar & simbol disederhanakan sebagai tulisan & pertanda. Lambang-lambang fragmental segera menjadi pengubah cara hidup. Manusia berani keluar gua, membangun kota dan peradaban, membarui semesta menjadi landskap tekstual yg mampu dibaca, dikendalikan & ditata.
Manusia berkebudayaan sudah membarui pengalaman membaca yang intuitif pada gua-gua sebagai instrumen komunikasi. Membaca lalu kehilangan spontanitasnya, juga kehilangan kekuatan intuitifnya yg sanggup memanggil semesta. Masyarakat bukanlah kelompok pemburu gua yang berkumpul pada sekeliling api unggun. Masyarakat dibangun sang daya-daya artifisial, kepercayaan , politik, kebudayaan, kenangan-kenangan akan peperangan, batas-batas geografis, kepentingan-kepentingan ideologis, ekonomi, konstitusi, menggunakan konsekuensi yg efektif menafikan nilai individu. Konstituen rakyat bukanlah individu melainkan daya-daya artifisial tersebut. Individu wajib bisa membaca, menginternalisasi daya-daya artifisal tadi untuk mampu terhindar berdasarkan ketiadaan; suatu ketiadaan artifisial, non person, kehilangan pengakuan apabila individu nir mampu membaca teks konstituen masyarakat: kepercayaan , politik, ideologi dan seterusnya.
Membaca yang sebenarnya
Alberto Manguel yang memperkenalkan dirinya sebagai pembaca, menulis tentang perbedaan antara Pinocchio (Collodi 1883) dan Alice (Lewis Carroll, 1865) dalam membaca. Pinocchio boneka kayu miskin namun bercita-cita tinggi dengan segala nasib buruknya ia berusaha bersekolah supaya bisa membaca dan pada gilirannya bisa hidup layak dan diakui resmi dalam masyarakat. Alice di lain pihak adalah gadis kecil yang bertualang karena rasa penasaran yang kuat terhadap kelinci sedang bergegas. Petualangan Pinocchio tidak menyuguhkan cerita tentang pengalaman membaca selain prestasi belajarnya yang baik dan membuat teman-temannya iri hati. Alice sebaliknya berkutat dengan pengalaman eksistensial tentang kebenaran dan realitas dirinya akibat permainan makna kata dan tutur bahasa yang begitu majemuk, non-singular dan tidak stabil.
Pinocchio mewakili hampir seluruh anak korban metodologi pembelajaran saat ini, yakni sekadar buat melaksanakan transfer ilmu pengetahuan. Kita bersekolah & mengambil spesialisasi buat mampu membaca dengan keterampilan tertentu & menerima kiprah yg sesuai pada masyarakat. Menjadi juara, memenangkan medali olimpiade matematika atau fisika adalah kemewahan yg sangat diharapkan orang tua dalam anaknya. Pinocchio yg sebagai brutal & nakal kemudian mengalami banyak sekali nasib tidak baik lantaran menghindari sekolah yang memberi pesan moral buat beretika terpelajar pada anak-anak.

Kisah Alice pada lain pihak menggemakan kembali pengalaman kebahasaan yang sangat imajinatif pada dalam gua-gua purba nenek moyang kita. Berbahasa merupakan berdaya cipta, berkreasi, bermain menggunakan pengalaman, mengembangkan kekayaan batin & memperkaya ruang-ruang simbolik pada pada kehidupan.
Bagi Pinochio, membaca adalah mengeja pertanda, lambang-lambang yang diturunkan masyarakat ke kitab -kitab sekolah agar ia mampu sebagai seperti yang diperlukan, sebagai person, eksklusif yg diterima pada rakyat.
 Bagi Alice, membaca itu intuitif, menebak, mencari pada kegelapan gua loka bahasa dilahirkan. Membaca bukanlah buat menjadi individu pandai , berkepribadian dan terpelajar, melainkan buat bermain menggunakan semesta, menemukan kembali khayalan, mencari makna-makna yg tak terhingga pada balik kata-istilah berdaya cipta. Alice nir memperoleh tugas apapun untuk sebagai anak insan, nir misalnya Pinocchio. Membaca berarti berada secara spontan pada hadapan rahasia semesta.
Bagi Alice, membaca itu intuitif, menebak, mencari pada kegelapan gua loka bahasa dilahirkan. Membaca bukanlah buat menjadi individu pandai , berkepribadian dan terpelajar, melainkan buat bermain menggunakan semesta, menemukan kembali khayalan, mencari makna-makna yg tak terhingga pada balik kata-istilah berdaya cipta. Alice nir memperoleh tugas apapun untuk sebagai anak insan, nir misalnya Pinocchio. Membaca berarti berada secara spontan pada hadapan rahasia semesta.
Ketegangan antara dunia Parmenides dan global Heraclitus, kecemasan akan runtuhnya nilai-nilai dampak perubahan pesat, merupakan kecemasan masyarakat. Membaca ala Pinocchio akan menenangkan masyarakat namun merugikan humanitas yang bebas. Membaca seperti Alice, adalah menelusuri daya naratif humanitas kita. Manusia bukanlah elemen ideologis, pion kepercayaan , unsur kebudayaan atau obyek ekonomi yang membangun warga . Manusia itu, tiap-tiap kita adalah sebuah buku, narasi, dinamis & berharga sebagai bacaan yang senantiasa baru. Individu naratif inilah yang mengatasi polemik Heraclitus & Parmenides. Narasi senantiasa berubah & senantiasa mengenai kebenaran keberadaan kita dalam semesta.
 |
Caption : Siapa engkau.. realitas diri dan semesta yang senantiasa berubah.. metamorphing |


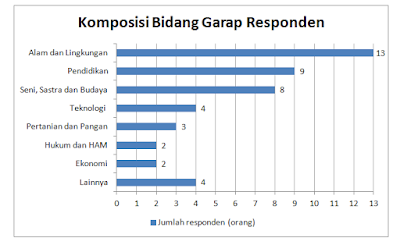

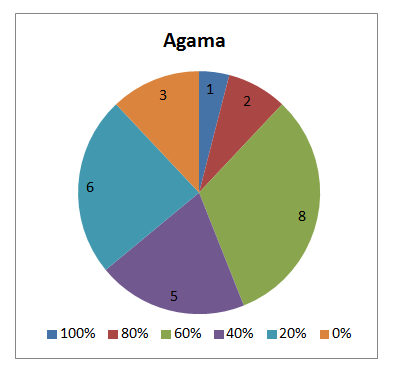










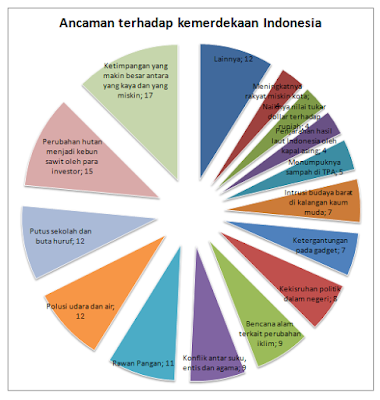










 Bagi Alice, membaca itu intuitif, menebak, mencari pada kegelapan gua loka bahasa dilahirkan. Membaca bukanlah buat menjadi individu pandai , berkepribadian dan terpelajar, melainkan buat bermain menggunakan semesta, menemukan kembali khayalan, mencari makna-makna yg tak terhingga pada balik kata-istilah berdaya cipta. Alice nir memperoleh tugas apapun untuk sebagai anak insan, nir misalnya Pinocchio. Membaca berarti berada secara spontan pada hadapan rahasia semesta.
Bagi Alice, membaca itu intuitif, menebak, mencari pada kegelapan gua loka bahasa dilahirkan. Membaca bukanlah buat menjadi individu pandai , berkepribadian dan terpelajar, melainkan buat bermain menggunakan semesta, menemukan kembali khayalan, mencari makna-makna yg tak terhingga pada balik kata-istilah berdaya cipta. Alice nir memperoleh tugas apapun untuk sebagai anak insan, nir misalnya Pinocchio. Membaca berarti berada secara spontan pada hadapan rahasia semesta.












