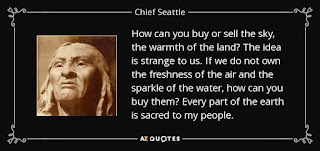Oleh: Angga Dwiartama
Pendahuluan
Sekarang, aku tidak perlu lagi risi soal kekurangan kuliner di malam hari. Cukup pilih majemuk hidangan pada pelaksanaan gawai pandai saya, & dalam 15-30 mnt, seorang akan mengetuk rumah saya membawa sebungkus makanan. Tidak perlu keluar uang tunai, lantaran seluruh pembayaran telah dilakukan di pelaksanaan pandai saya. Saya juga nir perlu khawatir waktu berkelana seorang diri ke daerah antah berantah. Tanyakan saja pada Google Maps, dan dia akan memberitahukan majemuk alternatif jalan buat ditempuh, termasuk jalan-jalan tikus, bersama perkiraan ketika tempuhnya.
Ini jelas belum seberapa. Petani di AS, Australia atau Eropa sana bekerja laiknya manajer kantor, mengendalikan semua aspek pertanian dari komputer pintarnya di ruang kantornya yang sempit. Sensor mendeteksi kadar air tanah dan kelembaban udara, misalnya, dan menginstruksikan sprinkler untuk menyemprot air secara otomatis apabila dianggap terlalu kering. Pestisida dan herbisida sudah tidak diperlukan lagi, karena setiap hama dan gulma dapat dideteksi oleh sensor dan ditembak menggunakan laser. Di peternakan, setiap ekor domba yang digencarkan di lahan memiliki taggeospasial di telinganya yang sinyalnya ditangkap oleh satelit, sehingga perilaku domba yang sedikit berbeda saja dari gerombolannya dapat dianggap sebagai kelainan. Pesawat tanpa awak kemudian akan melihat lebih jelas apa yang terjadi dan melaporkan temuan lapangan melalui foto atau video ke sang manajer. Tersadar untuk bergerak, sang manajer memasukkan koordinat si domba ke motor ATV-nya, dan motor tersebut akan membawa petani untuk mengunjungi ternak tersebut dan memberi perlakuan[1].
Menyongsong revolusi industri 4.0
Yang kita saksikan saat ini adalah apa yang disebut revolusi industri 4.0, era yang (katanya) ditandai dengan perubahan di berbagai sektor kehidupan, dimana teknologi komputasi, sistem informasi, robotik, bioteknologi, dan nanoteknologi berjalin erat dalam keseharian kita. Kita menghadapi era yang (katanya lagi) akan mengubah cara kita berpikir, merasakan, bergerak dan hidup. Kita menyambut revolusi industri 4.0 layaknya rakyat jelata bersorak menyambut pahlawan perang. Ini adalah solusi bagi semua permasalahan dunia, katanya. Bayangkan saja, di saat diskursus tentang revolusi hijau, kerusakan lingkungan, deforestasi, atau pangan beresiko turunan GMO berkumandang, teknologi dalam industri 4.0 menawarkan narasi alternatif: Bertani bisa lebih ramah lingkungan tanpa pestisida dan pupuk sintetis berlebih apabila kita menerapkan smart atau precision farming, sistem monitoringpintar berbasis satelit bisa dipakai untuk mengidentifikasi titik-titik api dan mencegah kebakaran hutan, kita bisa hidup lebih sehat tanpa obat-obatan kimia apabila kita bisa memonitor denyut jantung, kadar gula atau kolesterol secara terotomasi, atau bahkan memetakan setiap gen di DNA kita untuk memastikan kalau kita tidak punya penyakit turunan berbahaya. Semuanya jadi lebih sehat, alami, dan ramah lingkungan; semuanya, tentunya, kecuali teknologi itu sendiri.
 |
| Era industri 4.0 |
Tapi, apa sih revolusi industri 4.0 itu? Dan ke mana perginya revolusi industri yang lain? Kejutannya, tidak ada yang benar-benar bisa menjawab dengan pasti. Adalah Angela Merkel, Konselor Jerman, yang di tahun 2011 dihadapkan pada tantangan pembangunan industri di Eropa, dan Jerman memiliki dana besar untuk memfasilitasi itu. Beberapa pemikir menawarkan gimmickyang menarik: revolusi industri 4.0 adalah the next big thing di industri, dalih mereka. Mereka membandingkannya dengan tahap revolusi industri pertama yang bertumpu pada mesin uap dan batubara, revolusi industri kedua yang dicirikan oleh assembly line gaya pabrik mobil Ford (yang selanjutnya dikenal dengan Fordism) untuk produksi massal, revolusi industri ketiga pada sistem otomasi di pabrik-pabrik besar, menggantikan buruh pabrik dengan mesin-mesin industri, dan revolusi industri 4.0 dengan semua yang berhubungan dengan komputasi, internet, big data, dan (sekali lagi) internet! Dana besar pun digulirkan ke universitas-universitas dan lembaga penelitian untuk semua bentuk penelitian yang berhubungan dengan “komputer dan internet”, atau bahasa kekiniannya, Internet of Things(IoT). Amerika Serikat, walau berjalan di atas langkah yang sedikit berbeda (karena Silicon Valley dan sektor swasta lebih dulu merajai industri 4.0), pun bermuara ke sungai yang sama.
Hanya dalam waktu kurang dari satu dasawarsa, kita sudah bisa menyaksikan gaung industri 4.0 di hampir seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, yang dengan tegapnya menjadi pasar bagi ratusan platform startup digital yang mencakup sektor-sektor penting: perdagangan, pertanian, kehutanan, pendidikan, kesehatan, tata kota, pariwisata dan lingkungan hidup. A.T. Kearney, Lembaga riset ekonomi internasional, menunjukkan bahwa di tahun 2017, pertumbuhan investasi startup digital meningkat hingga 68 kali lipat dalam waktu lima tahun, dengan total investasi senilai 3 milyar US Dollar di lebih dari 2000 startup digital di Indonesia saja. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan pengguna internet yang mencapai 143 juta orang lebih (JakartaGlobe, Februari 2018). Di kampus saya saja, setiap program studi diminta untuk bisa menyisipkan kata kunci seperti Big Data dan Artifical Intelligence di dalam kurikulumnya. Jadi kini kami punya jargon-jargon seperti smart farming, smart city, smart classroom, smart politics, smart architecture, dan berbagai smart lainnya.
Sebuah delusi?
Nyatanya, seperti diprediksi, revolusi industri 4.0 memang mengubah banyak aspek dalam kehidupan kita. Saya jadi lebih peka terhadap kesehatan saya; saya gelisah kalau hari ini belum berjalan 10.000 langkah dalam catatan fitbit saya. Hubungan saya dengan teman-teman berubah karena tetiba orang yang saya pikir saya kenal bersuara tentang hal yang sama sekali asing di akun Facebooknya. Saya sekarang lebih mementingkan berapa likes yang saya terima hari ini ketimbang berapa banyak pekerjaan yang saya selesaikan. Di tengah realitas revolusi industri 4.0 sekarang ini, kita juga perlu sadar bahwa ada lebih banyak lagi hal yang tersembunyi di balik semua hal yang berbau digital dan internet. Revolusi industri 4.0, saya boleh bilang, adalah realita dan juga ilusi.
Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ilusi (n) sebagai “pengamatan yang tidak sesuai dengan pengindraan”. Cambridge Dictionary menawarkan dua pengertian, “an idea or belief that is not true” atau “something that is not really what it seems to be”. Pada ilusi, apa yang kita tangkap di indera kita belum tentu apa yang sebenarnya. Hal ini berarti bahwa ada sesuatu yang lebih besar lagi dari apa yang kita pahami tentang satu realita tersebut. Ilusi berakar pada ketidaksadaran kita pada realita. Kita mempersepsikan bahwa ilusi adalah realita itu sendiri. Erich Fromm, seorang sosiolog/psikolog asal Jerman, di dalam bukunya Beyond the Chains of Illusion, memaparkan bahwa saat kita menangkap ilusi sebagai realita, kita akan cenderung terjerat dalam ilusi tersebut. Bayangkan film the Matrix, di mana para penghuninya menikmati hidup layaknya itu sebuah realita – sampai akhirnya mereka memilih pil merah!
 |
| Film Matrix |
Lalu, apa hubungan delusi dengan revolusi industri 4.0? Saya coba bahas setidaknya tiga hal yg mungkin bisa membongkar delusi industri 4.0:
Pertama, kita berbicara tentang ekologi. Industri 4.0 dicirikan oleh sistem komputasi dan internet nirkabel. Kita seringkali menganggap sepele hal ini. Tapi di balik kenirkabelan 4.0, terdapat infrastruktur fisik yang jauh lebih kompleks. Untuk setiap titik geografis di mana Anda bisa menikmati sajian 4G, terdapat infrastruktur besar seperti menara BTS, ruang penyimpanan data (server), dan jutaan pekerja yang menghasilkan handheld device Anda. Studi yang dilakukan oleh Costenaro dan Duer (2012) melaporkan bahwa di dalam setiap megabyte data yang dikirimkan, terdapat megawatts energi yang dikeluarkan. Katanya, untuk setiap GB data, dibutuhkan sekitar 5 kWh energi listrik. Sekarang kita lakukan sedikit perhitungan. Data A.T Kearney (2017) menyebutkan bahwa di Indonesia, terdapat sekira 150 juta orang yang terhubung dengan internet melalui gawainya. Dengan mengasumsikan saja bahwa setiap orang menggunakan 5 GB data per bulan, hal ini berarti bahwa setiap bulannya kita sudah menghabiskan sebesar lebih dari Rp. 5 triliun untuk menyelami dunia digital. Masalahnya, 62% dari energi (dan biaya) yang dikeluarkan ditanggung bukan oleh pengguna komputer atau gawai, tapi oleh pusat data dan saluran distribusi. Artinya, kita menemui kondisi seperti ‘tragedy of the common’, dimana karena terdapat lebih dari Rp. 3 triliun/bulan beban biaya energi yang tidak ditanggung oleh pemakai (eksternalitas), porsi ini menjadi common property yang terboroskan.
Sejalan dengan paparan energi di atas, perubahan gaya hidup akibat industri 4.0 tidak sepenuhnya mengurangi dampak negatif bagi lingkungan hidup. Sebut saja begini: sebelum e-commerceberkembang, saya harus berpikir dua kali untuk belanja. Ini tidak hanya karena saya mempertimbangkan pengeluaran saya bulan ini, tapi juga karena upaya yang dibutuhkan untuk berbelanja (keluar rumah, naik kendaraan, mengantre di kassa pembayaran) cukup menjadi penghambat gairah belanja saya. Kini, ketika teknologi membuat semuanya lebih efisien, kita tidak lagi memiliki mental barrier tersebut. Dalam konteks ini, efisiensi mendorong lebih tingginya perilaku konsumerisme. Tapi, apakah beban lingkungan aktivitas-aktivitas ini menjadi berkurang? Pada kenyataannya, arus pengiriman barang (melalui jasa kurir) malah semakin tinggi. Ojek online berkontribusi terhadap kemacetan jalan raya. Apabila kita hanya menghitung biaya yang tampak, jelas kesimpulannya adalah sistem 4.0 ini lebih efisien. Tapi kalau kita menginternalisasi semua eksternalitas lingkungan, saya curiga beban biaya industri 4.0 akan jadi lebih tinggi.
Kedua, kita berbicara tentang masyarakat. Saya kembali merujuk satu serial TV berjudul Persons of Interest, yang bercerita tentang sebuah program di supercomputer yang memiliki algoritma kompleks berdasarkan data pribadi setiap orang (profil media sosial, data jaminan sosial, rekening Bank, catatan kesehatan) dan memprediksi apakah seseorang berpotensi menjadi ancaman bagi negara. Terlalu dramatis dan berlebihan memang, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita sedikit banyak bergerak ke arah itu. Baru-baru ini, misalnya, diberitakan AI yang bisa memodelkan dan memprediksi kapan seseorang akan meninggal dunia. Big datamenjadikan manusia sebagai angka dan pola yang digunakan untuk kepentingan pemilik modal (atau juga pemerintah).
Gilles Deleuze, seorang filsuf ternama dari Perancis, menamakan masyarakat kita saat ini sebagai society of control, yang diatur, diawasi dan dikendalikan oleh kekuatan yang tersebar di masyarakat itu sendiri. Sebuah ramalan jitu dari tulisan yang disusunnya di tahun 1991, Deleuze memprediksi bahwa kekuatan untuk mendisiplinkan masyarakat tidak lagi terletak di tangan pemerintah. Menurut Deleuze, semua orang mengawasi orang lain, dan nantinya kita semua diawasi oleh perusahaan yang memiliki akses terhadap Big Data tersebut (sebut saja: Facebook). Hal yang mengikuti adalah bahwa informasi menjadi begitu banyak dan mudah diakses, tantangan masyarakat saat ini bukan lagi mencari informasi di ruang kosong, tapi mencari informasi yang tepat di antara milyaran data yang tidak relevan. Karena kita selalu ditawari dengan informasi (berharga dan tidak) di layar gawai kita, cara yang paling efektif untuk menyampaikan informasi adalah dengan membuat kita mau menoleh. Era ini yang kemudian dikenal dengan era ekonomi perhatian (attention economy). Masyarakat tidak butuh berita yang benar atau akurat, tapi berita yang bisa menangkap perhatian mereka. Konspirasi di balik peristiwa 911, kisah dramatis orangutan yang ditembaki dengan senapan, plastik yang terperangkap di perut bangkai paus yang terdampar di pantai – semua lebih cepat menarik perhatian kita dibandingkan pengetahuan yang mendasari itu (bioakumulasi, deforestasi, atau konflik). Tidak salah mungkin, apabila kita bisa mengemas pesan yang baik dengan catchphraseyang unik. Tapi yang saya khawatirkan adalah sebaliknya; ambil saja Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengeluarkan beratus cuitan di Twitter, tak peduli apa isinya, lalu dengan santainya menjawab, “I got your attention, didn’t I?”
Penutup
Terakhir, hal yang paling menjadi ilusi di Industri 4.0 adalah, bahwa sebagian besar masyarakat dunia, mereka yang tidak memiliki akses terhadap semua infrastruktur canggih ini, pada kenyataannya menjalani business as usual. Studi yang kami lakukan tentang dampak digitalisasi pertanian terhadap petani gurem sejauh ini menunjukkan bahwa industri 4.0 tidak sekuat itu memberi pengaruh positif. Banyak petani tidak memiliki atau bisa mengoperasikan gawai pintar, dan kalaupun punya, untuk apa? Ekonomi yang beredar mengelilingi mereka adalah ekonomi klasik yang melibatkan elite desa, bandar, tengkulak, rentenir dan ijon. Masuknya anak-anak muda untuk terlibat membantu para petani, bagi beberapa, tidak memberikan solusi, tapi justru menambah masalah baru. Rantai pasok bertambah panjang. Peran ijon digantikan oleh para startup ini. Kata sebagian, ijon mungkin masih lebih baik, karena toh mereka adalah juga warga lokal yang memiliki kedekatan psikologis, yang selalu bisa dimintai pinjaman untuk anak petani yang sakit atau akan menikah. Sama halnya di kota, dimana masyarakat miskin akan menjadi orang-orang terakhir yang belanja di pasar dan menaiki angkot menyusuri kota, kali ini dengan kepadatan lalulintas yang lebih dahsyat.
Saya bukan anti-pembangunan dan anti-teknologi. Menurut saya, peradaban akan selalu berkembang dalam laju yang kita tidak pernah bisa kita perkirakan (lagipula, siapa sangka teknologi yang diimpikan di Back to the Futurebisa terwujud juga di masa kini?). Meskipun demikian, kita harus sadar bahwa ilusi itu ada, dan menjadi panggilan kita untuk lepas (dan melepaskan yang lain) dari jeratan ilusi itu. Hanya dengan begitu maka kita akan bisa melihat segala kemajuan zaman ini dengan lebih bijak. Pada akhirnya, penting untuk diingat bahwa teknologi hanyalah perantara – yang bisa memecahkan masalah kemanusiaan bukanlah teknologi, tapi manusia itu sendiri.
Rujukan:
Costenaro, D., & Duer, A. (2012, August). The megawatts behind your megabytes: going from data-center to desktop. InACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings.
Deleuze, G. (1995). Postscript on control societies.Negotiations: 1972–1990, 177-82.
Fromm, E. (2001).Beyond the chains of illusion: My encounter with Marx and Freud (Vol. 780). A&C Black.
https://www.allaboutlean.com/industry-4-0/
Rujukan film:
The Matrix Trilogy (film layar lebar)
Persons of Interest (serial TV)
Back to the Future: Trilogy (film layar lebar)
[1] Coba saksikan keseruan smart farming system di sini: http://bit.ly/smartfarmvideo