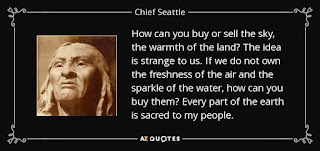Oleh : David Ardes Setiady
Hari itu kalender di smartphone menunjukkan tanggal 15 September 2017, ketika langit tampak cerah nan teduh, matahari memancarkan sinarnya sembari kawanan awan memberi kesejukan atas teriknya. Saya bersama dengan rombongan beranjak dari penginapan menuju pelabuhan Coron Harbour, sekitar 30 menit lamanya melintasi pemukiman padat yang pemandangannya seperti perkampungan di Indonesia. Setibanya di pelabuhan, sebuah perahu sudah menanti kehadiran kami karena memang sudah disiapkan oleh rekan-rekan Samdhana Institute Filipina dan kami pun segera memasukinya. Lalu, ada sedikit proses loading barang dan berbagai persiapan, di antaranya pemeriksaan oleh penjaga pantai memastikan jumlah penumpang yang berangkat agar sesuai dengan yang kembali nantinya, kemudian sang penjaga pantai juga memeriksa bahwa di dalam perahu tersedia rompi pelampung yang wajib dipakai para penumpang selama perjalanan. Tak lama, perahu pun segera mengarah menuju ke tujuan, Pulau Coron.
Perjalanan ini merupakan bagian menurut kegiatan workshop yang diselenggarakan sang Samdhana Institute pada rangka menyusun acara capacity building. Di sana sudah menanti komunitas suku Tagbanwa yang telah mendiami Pulau Coron sejak usang. Nantinya kami akan berinteraksi dengan mereka buat belajar tentang kehidupan mereka dan bagaimana sinergi dapat terjalin menggunakan Samdhana.
 |
| Foto suasana pada kapan (Dokumentasi Pribadi) |
Perjalanan menyeberang pulau ini memakan ketika sekitar 45 mnt, namun tidak begitu terasa karena pemandangan yg tersedia pada sekeliling bahtera begitu indah. Rasanya ingin terus mengabadikan setiap bagian berdasarkan pemandangan yang tersaji dari perahu ini, namun saya harus menyimpan daya baterai ponsel ini karena terdapat berbagai kegiatan dan pemandangan lain yang mampu jadi tidak terabadikan saat daya ponsel habis. Maka naluri sajalah yg menentukan buat merogoh pemandangan yg cocok pada hati.
 |
| Pemandangan saat bepergian berangkat menuju Pulau Coron (Dokumentasi Pribadi) |
Waktu yang mengalir tidak terasa ketika akhirnya perahu merapat ke dermaga sederhana di Pulau Coron. Kesederhanaan yang begitu serasi dengan keindahan alam yang terpahat di pulau ini, rasanya teknologi yang wah kurang pantas bersanding karena akan merusak kesahajaan yang terpancar. Rombongan pun segera mengarah ke lokasi pertemuan dimana telah menanti para tetua masyarakat Tagbanwa, yang komunitasnya bernama Tagbanwa Tribe of Coron Island Association (disingkat TTCIA). Ruangan itu tampak sudah melalui perjalanan panjang dan mencoba bertahan dengan kesederhanaannya dengan beberapa cat yang tampak sudah terkelupas. Ada beberapa bangku panjang yang tersedia, mungkin memang menjadi tempat nongkrong penduduk setempat yang bertugas mengelola kegiatan pariwisata. Tidak ada wifi di sini, pun sinyal internet dari provider lokal tidak mudah tertangkap, seolah kita dipaksa merendahkan hati menghayati kesederhanaan yang hidup di tempat ini. Listrik pun sepertinya tidak ada, hanya disediakan oleh sebuah generator yang tujuan penggunaannya tidak saya tanyakan pada saat itu.
 |
| Dermaga pada Pulau Coron (Dokumentasi Pribadi) |
Pertemuan tadi berlangsung guyub, para tetua dan rombongan saling berkenalan menggunakan bahasa Inggris seadanya. Toh, tidak ada yg perlu merasa membuat malu dengan bahasa yg memang bukan bahasa sehari-hari. Yang krusial, ada bisnis saling berkomunikasi dan tahu. Adalah sang mantan ketua desa bernama Rudolfo ?Kudol? Aguilar yang menjadi narasumber pada pertemuan ini yang akhirnya berlangsung selayaknya sebuah konferensi pers. Bapak ketua desa mendapatkan pertanyaan kemudian bercerita sebagai jawabannya. Secara garis besar , pembelajaran yang didapatkan oleh rombongan merupakan :
1. Perjuangan masyarakat Tagbanwa dalam mendapatkan kedaulatan wilayah adat mereka, lalu komitmen masyarakat untuk menjaga serta melestarikan adat beserta gaya hidup yang harmonis dengan alam. Perjuangan itu dimulai pada tahun 1985, ketika mereka membentuk Tagbanua Foundation of Coron Island (TFCI) dengan tujuan mengubah status lahan hutan seluas 7.748 ha sebagai wilayah adat mereka , sesuai dengan kebijakan Kementerian Kehutanan saat itu yang memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk mengklaim hak ulayat mereka. Selanjutnya perjuangan tersebut adalah mengembalikan kesadaran budaya dan identitas sebagai suku Tagbanua kepada seluruh anggota suku, terutama generasi muda, yang pada saat itu sudah mulai lupa kebiasaan adat istiadatnya. Para tetua merasa akan percuma nantinya, bila wilayah adat ini berhasil diklaim kembali, tetapi generasi mudanya tidak memahami pentingnya mengelola wilayah adat tersebut. Maka mereka pun membagi tugas dan peran, dimana sebagian mengorganisir masyarakat Tagbanua di sekitar pulau untuk menghidupkan lagi adat istiadat dan budaya suku. Sebagian lagi, melanjutkan perjuangan administratif ke pemerintah Filipina atas wilayah adat yang juga mencakup perairan di sekitar pulau. Dengan demikian, masyarakat Tagbanua juga berhak mengelola wilayah perairan sekitar pulau sesuai dengan kebijaksanaan nenek moyang yang harmonis dengan alam. Tahun 1998, setelah perjuangan panjang yang diinisasi oleh Rudolfo Aguilar, Certificate of Ancestral Domain Claim (CADC) akhirnya diberikan atas wilayah adat masyarakat Tagbanua yang akhirnya mencapai puas 24.520 ha, tidak hanya daratan namun juga perairan. CADC adalah semacam dokumen resmi berkekuatan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah Filipina yang menjamin hak atas sebuah wilayah adat kepada masyarakat setempat. Ref : http://pcsd.gov.ph/protected_areas/coron.htm
2. Pengelolaan pariwisata, dimana para pengunjung harus menaati peraturan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Peraturan tersebut dirumuskan oleh semacam dewan adat yang diisi oleh para tetua suku dengan pertimbangan kebiasaan adat istiadat yang mereka hidupi. Jadi secara tidak langsung, tamu diajak untuk menghargai tempat hidup masyarakat setempat.
Wilayah tata cara TTCIA meliputi holistik pulau Coron ini & beberapa kepulauan kecil yg berada pada sekitarnya, yang kebanyakan adalah daratan kecil yg nir dapat ditinggali oleh insan. Cerita usaha rakyat Tagbanwa buat mendapatkan balik hak norma mereka, tertuang dalam sebuah spanduk yang sengaja dicetak pada tiga bahasa (bahasa Inggris, Tagalog, Tagbanwa) agar bisa diketahui sang para pengunjung. Cerita tadi nir hanya dibagikan pada para pengunjung, tetapi terutama diteruskan kepada generasi muda mereka agar tahu bahwa usaha ini tidak akan pernah berakhir karena merekalah yang akan mempertahankan kelestarian wilayah adat ini.
 |
| Bapak Rudolfo Aguilar (Dokumentasi Pribadi) |
 |
| Sejarah usaha TTCIA (Dokumentasi Pribadi) |
Walaupun dikatakan sebagai masyarakat adat, tidak berarti mereka terbelakang karena juga mengenal teknologi yang berkembang di dunia saat ini namun memilih untuk tidak bergantung kepadanya. Sekilas hampir tidak ada yang ber-hape (handphone-red) ria saat kami berkeliling. Yang menggunakan hape juga kebanyakan adalah para pengoperasi perahu yang kebanyakan berasal dari luar pulau.
 |
| Pemandangan menuju Danau Kayangan (Dokumentasi Pribadi) |
 |
| Aktivitas di danau (Dokumentasi Pribadi) |
Dalam hal pengelolaan pariwisata, masyarakat Tagbanwa bersikap cukup terbuka terhadap kehadiran turis, tetapi menerapkan anggaran yg relatif ketat dan disiplin. Setiap rombongan akan didampingi sang penduduk setempat waktu berkeliling pulau. Adapun area yg dapat dieksplorasi sangatlah terbatas & mereka yg menetapkannya demikian. O iya, pulau ini pun mempunyai saat berkunjung yg telah ditetapkan, yakni menurut pukul 08.00 hingga menggunakan 17.00 waktu setempat. Di tempat ini juga tidak terdapat penginapan sehingga para pengunjung betul-betul hanya berkunjung. Pada saat itu kami hanya berkunjung ke 3 titik, yaitu : Danau Kayangan, Pantai Attuangan, dan Twin Lagoon. Dari galat seseorang rekan Samdhana Filipina yg memang mendampingi komunitas ini, para tetua adat Tagbanwa sebenarnya ingin membatasi jumlah pengunjung sehari sebagai 100 orang, namun perundingan berdasarkan pemerintah daerah membuat hal itu urung terjadi.
Ada beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh para pengunjung pada pulau ini, yakni :
- Wajib membawa rompi pelampung
- Dilarang berenang menggunakan sunblock kimiawi (hanya boleh pakai yang sunblock dengan bahan alami)
- Dilarang berenang tanpa rompi pelampung
- Wajib didampingi oleh pemandu setempat
Di sana mereka pula mencoba hayati tanpa menggunakan plastik, sehingga kita akan mendapati warung (satu-satunya) yang menjual kelapa belia tanpa ada sedotan. Jadi, kita harus minum dengan seolah kelapa itu merupakan gelas, kemudian setelah airnya habis dan kita ingin makan dagingnya, kita tinggal bilang sama si tukang buat membelah kelapanya. Si tukang akan berbagi sendok berdasarkan kulit kelapa buat membantu kita memakan daging kelapa yang lembut.
Dari sana, kami bertolak menuju pantai Attuangan buat melanjutkan sesi refleksi. Pantai ini nisbi nir banyak pengunjung, saat itu hanya terdapat tiga perahu lain & ombaknya jua termasuk kecil. Pun tidak ada hiburan buatan insan misalnya banana boat, speedboat, parasailing, dan mitra-kawannya. Jadi, loka ini benar-benar diperuntukkan bagi mereka, para penikmat alam. Tidak juga terdapat rumah makan yang menyajikan ala restoran barat, hanya terdapat warung sederhana, yang waktu itu kami hanya ?Meminta? Air panas buat menciptakan kopi yang dibawa sang galat seseorang rekan rombongan.
 |
| Pantai Attuangan |
 |
| Aktivitas kelompok di Pantai Attuangan |
Setelah sesi refleksi tuntas, kami bertolak ke Twin Lagoon yg terdiri dari batu-batu besar yang membuat perairan pada sana sangat hening. Lokasi ini nisbi ramai dikunjungi, tampak ada kurang lebih 6 perahu lain yg ditambatkan di lebih kurang perahu kami. Penariknya merupakan perairan yang tenang sebagai akibatnya nisbi nyaman buat berenang, pun menurut pemandu wisata menunjukkan atraksi melakukan formasi insan-kelabang, dimana para pengunjung diminta mengambang saling berkait, kemudian pemandu akan menarik rantai insan ini menyeberangi teluk kembar ini. Selebihnya, kita boleh bereksplorasi sendiri pada sekitar area tadi.
Hal lain yang mungkin perlu diketahui adalah di setiap perahu terdapat sebuah bilik yang bagi orang Indonesia dikenal sebagai kamar mandi, namun awak perahu menyebutnya sebagai CR, yakni comfort room. Di dalamnya air tidak selalu tersedia dan apabila habis, awak perahu akan mengambil air laut untuk kegiatan “bersih-bersih” (tentunya persepsi bersih akan menjadi sangat subjektif).
Puas berkegiatan pada Twin Lagoon, kami pun kembali ke Coron-Palawan, tempat dimana kami berdiam selama pada Filipina. Perjalanan pulang, walau jalurnya sama dengan berangkat, menyajikan pemandangan yg tidak kalah latif & selalu menggugah keinginan berfoto yg tidak henti-hentinya juga. Komposisi awan & matahari senja mungkin menjadi santapan juru foto pemandangan, ditambah gerak air laut yang tenang. Tentu saja, kita boleh hanya duduk menikmati terpaan angin yg ?Ditabrak? Sang bahtera dan melihat pemandangan yang mengiringi perjalanan.
 |
| Pemandangan saat perjalanan pulang dari Pulau Coron |
Perjalanan yang relatif singkat ini, meninggalkan kenangan & pembelajaran bagi aku , bahwa Pulau Coron adalah model pariwisata dimana pengunjung bukanlah raja yg dilayani sesuai gaya mereka. Melainkan, pengunjung merupakan saudara menurut jauh yg datang dan berkenan buat tahu dan mengikuti norma setempat dalam menikmati alam.
Kapan ya sanggup balik lagi?
 |
| Penulis di Pulau Coron, Filipina |
Catatan :
Perjalanan ini dalam rangka Workshop Capacity Development yang diselenggarakan sang Samdhana Institute dengan tujuan mengembangkan acara kerja organisasi buat bisa membantu penguatan rakyat dampingan mereka. Samdhana Institute merupakan sebuah organisasi non-profit yang mempunyai visi mewujudkan sebuah keadaan dimana keanekaragaman hayati, budaya, & spiritualitas dihargai dan mengatasi pertarungan berbasis lingkungan menggunakan adil & setara buat seluruh pihak. Lebih lebih jelasnya tentang Samdhana Institute bisa mengunjungi http://www.Samdhana.Org/